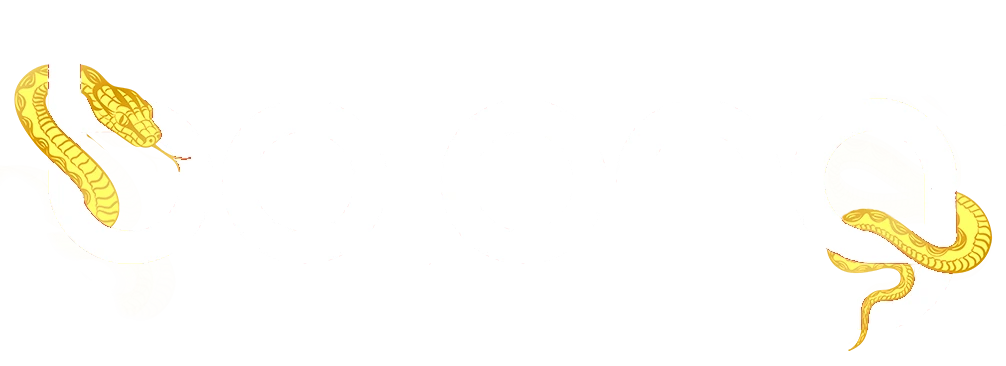Ilustrasi orang hokkian pada zaman dulu - Image from Internet. Segala keluhan mengenai hak cipta dapat menghubungi kami
Bolong.id - Kebanyakan orang Tionghoa yang ada di Indonesia adalah orang Hokkien, Hakka, Teochew, atau Kanton. Kelompok-kelompok tersebut berasal dari provinsi Fujian (Provinsi Hokkien) dan Guangdong (Provinsi Canton). Jika keduanya adalah Provinsi Hokkien dan Canton, di mana Hakka dan Teochew?
Hakka agak bisa diperdebatkan karena pada dasarnya- tidak, secara harfiah, mereka adalah ‘guest family' (客家人) mereka berasal dari Tiongkok Utara dan bermigrasi ke Selatan selama jatuhnya Dinasti Han Selatan sekitar 700 ratus tahun yang lalu. Sekarang, sebagian besar menetap di Guangdong dan Fujian.
Sementara Teochew berasal dari Guangdong Timur, wilayah Chaoshan. Agak sulit untuk membedakan bahasa Teochew dan Hokkien karena kesamaan fonetik, tetapi sebagian juga karena Teochew dianggap sebagai cabang dari bahasa Min Selatan, yang juga merupakan bagian dari bahasa Hokkien.
Dilansir dari medium.com, pada tahun 523 M selama Dinasti Utara dan Selatan, wilayah Chaoshan di Teochew direorganisasi menjadi bagian dari Fujian. Dari 523 M hingga 1575 M pada periode Dinasti Ming Akhir, wilayah Chaoshan adalah bagian dari provinsi Fujian.
Sejak saat itu hingga 1915 M, Era Republik Tiongkok, Chaoshan direorganisasi menjadi bagian dari provinsi Fujian dan Guangdong. Dari tahun 1915 dan seterusnya, Chaoshan menjadi bagian dari provinsi Guangdong.
Namun dalam artikel ini, akan lebih fokus pada orang Fujian pada khususnya. Orang Fujian dalam artikel ini, mengacu pada kedua kelompok dialek tersebut; 1) Hokkien, dan 2) Hakka.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wolfram Eberhard dan diterbitkan oleh University of California Press pada tahun 1965, ciri-ciri non-fisik yang dinyatakan sebagai karakteristik provinsi Fujian adalah klan yang picik, licik, dan suka mengambil risiko.
Stereotip lain orang Fujian yang pekerja keras, hebat dalam berwirausaha dan bisnis digeneralisasikan sebagai stereotip Tiongkok di negara lain, terutama di Indonesia. Orang Fujian tidak keberatan memulai dari bawah, bahkan sebagai pedagang kaki lima. Hal lain yang juga dicatat oleh orang-orang Utara di Tiongkok tentang orang Fujian adalah bahwa mereka lebih tertarik berbisnis daripada menjadi sarjana, penyair, atau filsuf.
Terisolasi secara geografis oleh perbukitan dan pegunungan membuat orang Fujian mengandalkan garis pantai dan pelabuhan mereka untuk berdagang, dan akhirnya membawa mereka ke belahan dunia lain, terutama Asia Tenggara.
Salah satu kota terpenting di Fujian yang menyumbang banyak migran ke Asia Tenggara adalah Quanzhou, kota pelabuhan yang terletak di bagian selatan Fujian. Orang-orang di kota ini telah pergi ke Asia Tenggara sejak Dinasti Tang (618 hingga 907), alasan utamanya karena keterbatasan lahan pertanian dan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka keluarga-keluarga di Quanzhou mengembangkan tradisi migrasi sebagai strategi keluarga untuk menghadapi kesulitan dan peluang untuk mencari nafkah.
Seorang musafir dari Zhangzhou, Cheng Rijie pergi ke Batavia pada tahun 1730, ia menulis bahwa Batavia memiliki banyak orang dari Zhangzhou, Quanzhou, dan Hu Guang dan bagi mereka yang berhasil dalam bisnis, mereka melakukan perjalanan ke sana dan kemudian kembali dengan membawa kapal yang penuh dengan barang. Meskipun mereka kemudian menjadi kaya, kebanyakan dari mereka kemudian melupakan kesulitan yang mereka hadapi. Setidaknya ada ratusan ribu orang seperti itu.
Pada akhir Ming hingga Dinasti Qing, terjadi jumlah emigrasi yang lebih besar. Di sini, segalanya menjadi kacau bagi orang Quanzhou dan orang Fujian. Pada Dinasti Ming hingga Qing, pemerintah memberlakukan serangkaian larangan laut yang disebut 'haijin' (海禁) atau kebijakan isolasionis yang membatasi perdagangan maritim swasta dan pemukiman pesisir.
Selama salah satu periode larangan pada tahun 1622, orang Fujian tidak begitu peduli, karena Belanda memahami keinginan orang Fujian untuk perdagangan dan migrasi, Belanda mempersenjatai diri dan berlayar ke Xiamen untuk menuntut otoritas Tiongkok untuk mengizinkan para saudagar Tiongkok untuk berdagang dengan mereka dan Belanda bahkan memberikan izin Fujian untuk datang dan tinggal di Batavia. Di sinilah pemerintah pusat di Beijing mulai mempertanyakan kesetiaan orang Fujian.
Pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi, ia memutuskan untuk segera menghentikan semua navigasi Tiongkok ke Asia Tenggara, terutama pedagang swasta Tiongkok yang beroperasi di sana. Dia bahkan memerintahkan armada kekaisaran untuk menyita semua kapal yang ditemukan membawa kargo terlarang, mereka yang dinyatakan bersalah melanggar larangan dapat diasingkan ke Manchuria yang terpencil.
Kangxi pernah mendorong perdagangan luar negeri swasta, kebijakan pintu terbuka 1648 menyebabkan perdagangan berkembang antara Tiongkok dan Asia Tenggara, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, kaisar semakin khawatir tentang keamanan dan pasokan makanan.
Ketidakpercayaan yang meningkat antara Han dan Manchu dan perluasan diaspora Tiongkok khususnya orang Fujian di Batavia dan Luzon — yang diduga sebagai surga pemberontak anti-Qing, semua itu meningkatkan kekhawatirannya tentang kelanjutan kebijakan perdagangan ini, dan akhirnya membuat keputusan untuk melarang perdagangan dengan Asia Tenggara pada tahun 1716.
Namun, jaringan perdagangan sudah merambah jauh ke dalam komunitas lokal, banyak keluarga menggantungkan hidup mereka pada industri ini. Larangan tersebut mengakibatkan masalah sosial-ekonomi baru bagi perekonomian pesisir.
Setelah pelarangan, jumlah kapal Tiongkok yang mengunjungi Batavia tiba-tiba turun dari delapan pada tahun 1716 menjadi dua pada tahun 1720 dan kemudian nol pada tahun 1723.
Pada masa pemerintahan Yongzheng, ia menuntut pejabat setempat untuk tidak mempercayai kata-kata mereka dan memberlakukan pengawasan bagi para pedagang Fujian yang kembali dari Asia Tenggara untuk memastikan kesetiaan mereka.
Tetapi ketidakpercayaan kaisar ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Qianlong, catatan pengadilan Qianlong menunjukkan dua insiden penganiayaan terhadap orang Fujian yang kembali dari Jawa. Para kaisar ini membayangkan orang Tionghoa perantauan sebagai orang yang biadab, seperti iblis, dan berbahaya, sehingga mereka tidak pantas mendapatkan simpati atau pengakuan kekaisaran.
Selama 'Geger Pacinan' di Batavia 1740 atau pembantaian orang Tionghoa di Batavia, sekitar 8.000 pria, wanita, dan anak-anak telah terbunuh, dan penjarahan, pembunuhan, dan pembakaran besar-besaran yang menghancurkan komunitas Tionghoa di ibu kota Indonesia saat ini.
Belanda takut bahwa laporan pembantaian akan menghentikan perdagangan yang menguntungkan dengan Tiongkok, atau mungkin lebih buruk, pembalasan militer dari pemerintah Qing, jadi Belanda mengirim utusan untuk mengirim permintaan maaf kepada kaisar, namun kaisar tidak peduli dengan pembantaian tersebut.
Karena orang Fujian tidak diakui oleh pemerintah daratan, provinsiisme mereka menjadi lebih menonjol. Sejarawan Belanda sering mengabaikan hal ini dan memandang orang Tionghoa di Hindia Belanda atau Tionghoa diaspora sebagai entitas yang homogen, padahal sebenarnya mereka heterogen dan datang dengan identitas provinsialisme yang berbeda dan lebih kompleks; yaitu Fujian dan Kanton. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement