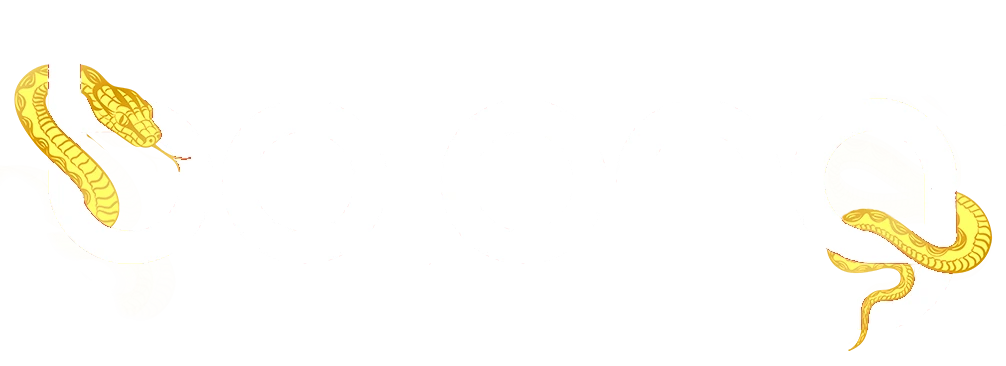bendera china - Image from Internet
Bolong.id - Di Indonesia masih terdapat kerancuan dalam menterjemahkan “Zhong Hua Ren Min Gong He Guo”, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai People’s Republic of China.Di kalangan institusi Pemerintah Indonesia, masih belum dibakukan apakah terjemahannya “Republik Rakyat Tiongkok" atau “Republik Rakyat Cina" atau “Republik Rakyat China”?
Sangat disayangkan bahwa di saat Indonesia sedang mengupayakan kebijakan luar negeri yang lebih terintegrasi dan terarah, kerancuan dalam penggunaan “Tiongkok”, “Cina”, dan “China” masih menjadi sebuah permasalahan yang mendasar. Apa mungkin memformulasi suatu kebijakan luar negeri yang komprehensif kalau secara internal masih ada perbedaan dalam mengidentifikasi target dari kebijakan itu sendiri?
Secara linguistik, istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” hanya ditemukan di Indonesia karena lahir dari pelafalan “Zhong Guo” (Negara Tengah) dalam Bahasa Indonesia dan dialek Hokien (yang digunakan di Provinsi Fujian, dari mana banyak etnis Tionghoa di Indonesia berasal). Kedua istilah tersebut tidak dikenal di negara-negara tetangga yang bahasanya juga mempunyai akar bahasa Melayu seperti Malaysia dan Brunei.
Pada permulaan Abad ke-19, masyarakat Tionghoa di Indonesia mengurangi penyebutan istilah “Cina” (pada saat itu ditulis “Tjina”) dalam berbagai publikasi dan percakapan publik karena dianggap merendahkan. Sebagai gantinya, istilah “Tiongkok” digunakan untuk penyebutan negara, dan “Tionghoa” untuk sebutan orang.
Pada tahun 1910, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan dan menyebut masyarakat Tionghoa dengan terminologi “Cina”. Hal ini dilihat oleh segenap masyarakat Tionghoa sebagai upaya untuk meletakkan status kelas komunitas mereka lebih rendah dari orang Barat dan Jepang.
Namun pada tahun 1928, Gubernur Belanda akhirnya mengganti penggunaan istilah menjadi “Tiongkok” dan “Tionghoa”.Sejak saat itu pula, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Ki Hajar Dewantoro, H.O.S. Tjokroaminoto, Sutomo dan Sukarno menggunakan istilah yang sama.
Pada saat pembukaan hubungan diplomatik di tahun 1950, dokumen resmi yang ditandatangi kedua belah pihak menggunakan terminologi “Republik Rakyat Tiongkok”, yang selanjutnya digunakan dalam segala persuratan resmi di antara kedua negara.
Trend penggunaan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” berubah setelah meletusnya peristiwa G30S-PKI dan semakin maraknya arus anti-Cina di tanah air. Dalam iklim politis yang kurang kondusif demikian, pada tahun 1966, Seminar Angkatan Darat ke-2 di Bandung dalam laporannya mengambil kesimpulan sebagai berikut:
“Demi memulihkan dan keseragaman penggunaan istilah dan bahasa yang dipakai secara umum di luar dan dalam negeri terhadap sebutan negara dan warganya, dan terutama menghilangkan rasa rendah-diri rakyat negeri kita, sekaligus juga untuk menghilangkan segolongan warga negeri kita yang superior untuk memulihkan penggunaan istilah ‘Republik Rakyat Tjina’ dan ‘warganegara Tjina’ sebagai ganti sebutan ‘Republik Rakyat Tiongkok’ dan warga-nya.”
Keputusan ini di sahkan oleh Presidium Kabinet Ampera pada 25 Juli 1967 dengan pertimbangan bahwa istilah tersebut adalah yang “disenangi rakyat Indonesia”. Kemudian diterbitkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 6 Tentang Masalah Cina, yang isinya secara spesifik melarang penggunaan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” karena nilai-nilai psikologis yang dianggap merugikan rakyat Indonesia.
Pada tanggal 6 Desember 1967, ditetapkan Inpres No. 14 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang tujuannya untuk semakin menekan kebebasan berekspresi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sejak itu, praktis tidak pernah lagi terdengar penggunaan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Yang ada hanya istilah “Cina”, yang walaupun secara tata bahasa dinilai netral, namun kerap digunakan dengan tendensi merendahkan.
Pada saat proses perundingan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara di tahun 1990, penyebutan People’s Republic of China dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu faktor perselisihan antara kedua pihak. Secara prosedural, Surat Presidium Kabinet Tahun 1967 masih melarang penggunaan istilah “Tiongkok”, sedangkan pihak Pemerintah RRT menilai penggunaan istilah “Cina” tidak merefleksikan itikad baik dari normalisasi hubungan diplomatik.
Mengingat kepentingan untuk merealisasikan normalisasi hubungan diplomatik, kedua belah pihak akhirnya setuju untuk menggunakan “Republik Rakyat China”, atau menggunakan ejaan “Cina” dalam bahasa Inggris. Dengan penulisan seperti ini, maka dalam pelafalannya, baik dalam bahas Inggris maupun Bahasa Indonesia, Tiongkok disebut dengan “cai.na”.
Dapat dimengerti alasan dari kompromi ini. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah status istilah “China” dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke-empat tahun 2008, istilah “Cina” tetap dieja tanpa hufu “h” dan dibaca “Ci.na”, bukan “Cai.na”. Selain itu, penjelasan mengenai “Cina” adalah “1. sebuah negeri di Asia; Tiongkok; 2. Bangsa yg tinggal di Tiongkok; Tionghoa”.
Oleh karena itu, penggunaan istilah “China” (baik dalam penulisan maupun pelafalannya) dapat dilihat seandainya memaksakan istilah bahasa Inggris “China” ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini mungkin bisa saja diterima. Tapi kalau begitu, kenapa Inggris bukan England, Belanda bukan Holland, Perancis bukan France, dan sebagainya?
Pada awal masa reformasi di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pencabutan atas Inpres No. 14 Tahun 1967 yang dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan norma-norma reformasi. Akan tetapi, Surat Presidium Kabinet Ampera No. 6 Tahun 1967 (mengenai pelarangan penggunaan istilah-istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”) tidak turut dicabut.
Presiden Wahid adalah salah satu tokoh reformasi yang memelopori penggunaan kembali istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Di dalam laporan kerja Pemerintah bulan Agustus 2000, Presiden Wahid sudah secara tegas menggunakan sebutan “Republik Rakyat Tiongkok”. Presiden Megawati Soekarnoputri juga melakukan hal yang serupa pada masa kepemimpinannya. Trend ini nampaknya yang ingin diteruskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan diplomasi dengan RRT sekarang.
Penggunaan istilah “China” seharusnya tidak lagi digunakan karena tidak sejalan dengan tata bahasa Indonesia yang baik. Istilah “China” memang sebuah kompromi yang telah diterima oleh pihak RRT. Tetapi komitmen terhadap persahabatan dengan RRT tidak harus dilakukan dengan mengorbankan integritas identitas nasional Indonesia, yang dicerminkan oleh penggunaan bahasa yang baik dan benar.
Istilah “Tiongkok” dibenarkan dalam tata bahasa Indonesia dan selama ini terbukti dapat juga diterima oleh pihak RRT. Namun demikian, secara hukum, penggunaan “Tiongkok” masih tidak diperbolehkan karena Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 6 tahun 1967 belum dicabut. Oleh karena itu, mungkin diperlukan upaya untuk mencabut produk hukumOrde Baru yang cenderung diskriminatif ini.
Memang, bagi banyak pihak, istilah-istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” sepertinya tidak lazim didengar. Namun demikian, istilah-istilah ini tidak pernah punah dari Bahasa Indonesia. Hanya saja, penggunaannya selama ini “diharamkan” oleh kondisi politik dan instruksi pemerintahan Orde Baru yang tidak simpatik terhadap Tiongkok.
Pelurusan terhadap penyebutan “Zhong Guo” dalam bahasa Indonesia memang bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam satu malam. Upaya ini juga belum tentu dapat dilakukan di kalangan masyarakat umum mengingat telah mendarah-dagingnya istilah “Cina” dalam psikologi rakyat Indonesia secara umum.
Namun demikian, demi mengupayakan kesamaan dalam upaya berdiplomasi dengan salah satu mitra terpenting Indonesia di kawasan, maka diperlukan terminologi yang serasi.
Memang patut dipahami permohonan Pemerintah RRT untuk tidak digunakannya istilah “Cina”. Namun demi integritas bangsa Indonesia, penggunaan istilah “China” (dengan pelafalan “cai.na”) seharusnya juga tidak dibenarkan.
Proses demokrasi dan reformasi terus bergulir, menciptakan Indonesia baru yang modern dan percaya diri. Demokrasi dan reformasi juga meningkatkan persahabatan yang harmonis antara segenap masyarakat di dunia. Perubahan juga layaknya ditujukan kepada upaya membangun diplomasi yang lebih canggih dan memegang teguh prinsip “million friends, zero enemy”.
Berdasarkan pemikiran ini, maka seharusnya tidaklah menjadi permasalahan bagi kita untuk kembali menggunakan sebutan “Tiongkok” sebagaimana tertulis pada Perjanjian Pembukaan Hubungan Diplomatik Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tahun 1950.(*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement